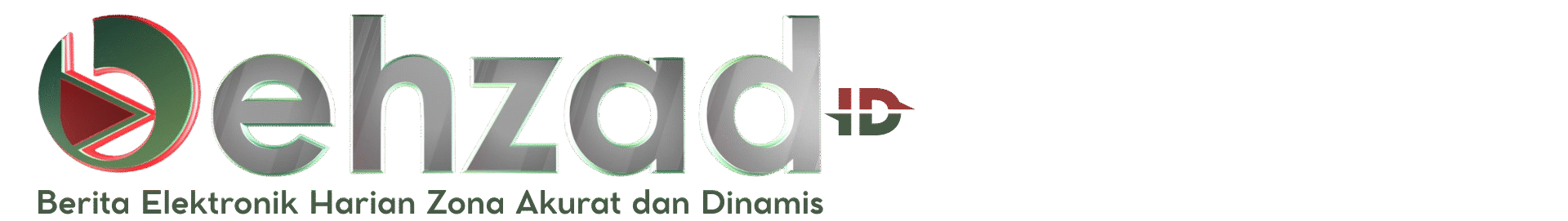Makassar — Setiap kali nama besar di dunia investasi digital terseret kontroversi, reaksi publik nyaris selalu terbelah dua. Ada yang marah besar, ada pula yang membela habis-habisan. Media sosial pun berubah menjadi “pengadilan dadakan”, penuh tuduhan dan pembenaran.
Namun di balik hiruk-pikuk itu, ada persoalan yang sering luput dibahas. Kasus yang menyeret nama Timothy Ronald seharusnya tidak hanya dibaca sebagai masalah individu, melainkan sebagai cermin rapuhnya ekosistem investasi digital di Indonesia.
Dalam satu dekade terakhir, dunia keuangan mengalami perubahan besar. Aplikasi investasi hadir di ponsel, istilah cuan, financial freedom, hingga passive income menjadi bahasa sehari-hari. Influencer keuangan pun muncul sebagai rujukan utama jutaan orang.
Masalahnya, di tengah euforia tersebut, batas antara edukasi dan promosi semakin kabur. Investasi sering dipresentasikan sebagai jalan pintas menuju kekayaan, bukan aktivitas yang sarat risiko. Literasi keuangan pun direduksi sekadar keberanian ikut tren, bukan kemampuan memahami ketidakpastian.
Di titik inilah komunitas investasi berbayar tumbuh subur. Mereka menawarkan kepastian di tengah risiko dan harapan di tengah kecemasan ekonomi. Narasinya sederhana dan menggoda: siapa pun bisa sukses asal mengikuti sistem. Jika gagal, kesalahan dialihkan sepenuhnya ke individu.
Pola ini berulang. Influencer memamerkan kisah sukses dan simbol kemewahan, diperkuat testimoni selektif. Sementara cerita kegagalan tenggelam atau dianggap bagian dari proses belajar. Keuntungan dinikmati segelintir pihak, risiko ditanggung bersama.
Popularitas di media sosial juga kerap disalahartikan sebagai keahlian. Jumlah pengikut dianggap bukti otoritas, padahal popularitas tidak selalu sejalan dengan kompetensi dan etika edukasi keuangan. Ketika otoritas dibangun oleh algoritma, ruang dialog kritis pun menyempit.
Terlepas dari proses hukum yang berjalan, kasus Timothy Ronald semestinya menjadi momentum refleksi bersama. Bukan untuk sekadar mencari siapa yang salah, melainkan membenahi budaya finansial yang terlalu mudah tergoda janji kepastian.
Regulasi memang penting, tetapi tidak cukup jika hanya hadir setelah kerugian terjadi. Yang lebih mendesak adalah membangun nalar kritis publik: memahami bahwa tidak ada imbal hasil tinggi tanpa risiko, dan tidak ada satu figur pun yang layak dijadikan otoritas tunggal.
Selama literasi keuangan dipahami sebagai jalan pintas menuju kaya, industri yang menjual harapan akan terus menemukan pasarnya. Yang dibutuhkan publik bukan janji cuan, melainkan keberanian untuk bertanya dan bersikap kritis.